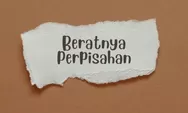Ia ikut mendidik anak-anak dengan pola didik dan motivasi yang tinggi. Ia juga mendukungku untuk sekolah lagi, ke luar negeri, lalu meneruskan doktoral di UI.
Meski pada awalnya, aku begitu sulit meyakinkan dia bahwa aku akan bisa membagi waktu untuk karir dan keluarga.
Wijaya adalah suami tanpa cacat. Kecuali setelah hari ini, kematian menjemputnya dalam diabetes yang akut, kutemui seorang perempuan tak kukenal dengan kerudung dan kain yang begitu sederhana, tergugu pada ujung kuburnya.
Matanya memerah sembab karena air mata yang tak kunjung henti membasahi pipinya hingga membekas pada kerudungnya.
Baca Juga: Inspirasi Liburan Anti Mainstream, Inilah Lima Tradisi Unik yang Harus Kamu Ketahui!
“Maaf, siapakah anda?” tanyaku ketika seluruh takziyah telah pergi kecuali anak-anak laki-lakiku.
Perempuan itu mendongakkan kepala, sehingga matanya tepat menghujam pada mataku. Sejenak kami bertukar energi yang sulit diterjemahkan dalam kata-kata.
Kemudian aku yang terkalahkan sebab perempuan itu begitu tulus. Kualihkan pandanganku pada kamboja yang berderai sebab angin memutar batang bunganya kemudian membuatnya terapung indah sebelum teronggok pada tanah pekuburan yang dingin.
“Saya.. saya.. Sholihah, Bu. Saya…”
Perempuan itu kembali tergugu. Jemarinya meraup tanah pekuburan suamiku, seperti merasa begitu kehilangan. Hatiku yang perempuan begitu tergetar.
Ada rasa aneh menjalari tepi-tepinya, kemudian menghujam memberi nyeri yang tiada tara. Tetapi aku perempuan rasional, aku tidak biasa dengan prasangka.
Maka kuhela nafas dalam-dalam dan sedikit mendongakkan dagu untuk menata kembali perasaanku yang tiba-tiba terasa lemah.
“Apakah Anda kerabat suami saya?” Perempuan itu terdiam.
“Atau Anda adiknya yang tidak pernah diperkenalkan kepada saya barangkali?” desakku tak sabar.