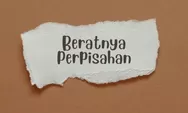“Dia perempuan baik-baik, Mara,” tutur Han, sahabat dan tangan kanan Wijaya, suamiku.
Aku melengos mendengar kata-katanya.
“Kau pasti ikut menjadi sponsor pernikahan mereka. Aku merasa dikhianati, Han, kenapa setelah sekian tahun mereka menikah, aku dan anak-anak tidak diberitahu? Bahkan setelah dia meninggal!” sengatku.
“Wijaya mencintaimu Mara, teramat sangat…”
“Omong kosong, jika memang cinta, mengapa harus membaginya dengan perempuan lain?”
“Justru karena ia mencintaimu dan tidak ingin melukaimu, ia menikahi Sholihah diam-diam.”
“Logika macam apa itu Han??” sergahku nyaris terpekik.
“Sholihah perempuan janda yang ditinggal mati suaminya, sebab berjihad saat peristiwa DOM di Aceh. Wijaya bertemu dengannya saat menjemput dana dari Malaysia. Ia sempat mampir ke Aceh untuk memberikan sedikit bantuan.
Sholihah begitu sederhana dan pantas untuk ditolong. Ia tidak menuntut apa-apa. Lagipula Wijaya menikahi Sholihah ketika ia sudah berusia lanjut, kenikmatan macam apa yang diharapkan pada pernikahan usia lanjut, kecuali ketentraman?”
“Maksudmu aku tidak bisa mendatangkan ketentraman pada suamiku?” sengatku sekali lagi.
Han mengangkat bahu. Sambil menggeleng-gelengkan kepala ia meninggalkan aku tanpa suara. Sedikit yang kudengar dari gumamannya: dasar keras kepala.
Aku terdiam dan merenungi kata-kata Han yang terakhir. Ketentraman. Apakah artinya itu bagi suamiku? Apakah beristrikan seorang wanita karir seperti aku mendatangkan ketidaktentraman?
Kapan aku berhandai-handai bersama Wijaya menikmati masa tua? Akhir-akhir ini aku justru sibuk meraih gelar doktorku. Kapan terakhir aku bisa memijit tengkuk suamiku?
Rasanya sudah lama sekali aku tidak melakukannya, sejak aku memutuskan untuk bekerja kembali pada sebuah penerbit majalah wanita yang memiliki deadline satu pekan sekali.
Aku bahkan tidak sempat menemaninya minum teh pada sore hari sambil duduk-duduk di serambi. Kemudian kesibukan itu bertambah ketika aku menempuh pendidikan strata dua dan tigaku berturut-turut di luar negeri.