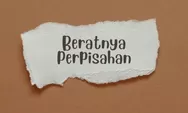Kami membutuhkan diskusi panjang lebar dan berbulan-bulan sebelum Wijaya mengizinkanku pergi. Kuingat kata-katanya yang terakhir kala itu.
“Ok, pergilah, Mah. Tidak pantas Papah mencegah kepergian Mamah jika memang kecerdasan Mamah dan ketrampilan yang Mamah miliki bisa membantu kemaslahatan dakwah dan umat Islam. Tetapi Papah tetap akan terus diperhatikan, bukan?”
Tak terasa ada yang dingin menyembul pada ujung mataku. Membuat pandanganku mengabur, sehingga aku tidak bisa menikmati lukisan awan berserabut pada jendela. Aku menangis.
”Maafkan aku, Mas…”
“Maah,” sebuah panggilan membuyarkan lamunanku.
“Adi, masuk, masuk sayang,” kupersilakan si Bungsu masuk ke dalam kamarku.
“Bulik Sholihah ingin bertemu, boleh?” tanyanya ketika memasuki kamar dan duduk di tepi ranjangku.
Aku terdiam. Segala yang sunyi berubah menjadi gempita yang guruh dalam dadaku. Ia, perempuan itu mau menemuiku? Betapa beraninya ia?
Logika ilmiahku kupaksa untuk memasung perasaanku yang tidak nalar. Mencemburui seseorang yang sudah tiada adalah perilaku yang paling bodoh.
“Ya tentu, tentu saja boleh,” aku seperti tidak bisa mendengar suaraku sendiri. Seperti datang dari dunia yang aku tidak mengerti. Aku tidak kuasa menatap matanya. Perempuan itu.
Maka tatapanku lurus menembus tubuhnya, meneropong nadi darah dan serabut kulitnya, lalu terhenti pada jarak yang jauh. Aku tidak kuasa menatap matanya, sebab aku menemukan mata suamiku di sana.
“Maafkan, maafkan saya, Bu. Saya tidak bermaksud me.. melukai keluarga ini dengan muncul di pemakaman.”
“Panggil.. panggil saya ‘Mbak’ saja. Ya, panggil saya ‘Mbak’,” kataku sambil menyimpan gemuruh.
“Bapak Wijaya sangat mencintai Ibu, beliau hanya sebulan sekali menginap di rumah kami. Beliau sangat membantu keluarga kami. Beliau menopang ekonomi kami sehingga penderitaan kami terkurangi.”
Ia tetap saja memanggilku ‘Ibu’.