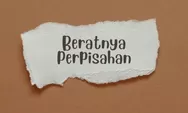Belum separuh perjalanan terlewati rasanya napasku sudah hampir habis. Aku memang jarang sekali berolahraga, jadi berjalan menaiki bukit seperti ini membuatku payah.
Teman-temanku sudah berjalan lebih dulu di depan, sebagian anggota Merti Buwana yang menjadi pendamping bahkan sudah ada yang sampai atas dan mulai menanam bibit pohon, sementara aku harus berkali-kali berhenti untuk menata napas kembali.
“Keira masih kuat?” Kei mucul lagi di depanku. “Kalau nggak kuat berhenti di sini aja, jangan dipaksa,” lanjutnya.
Baca Juga: Cerpen Inspiratif: Sebuah Kisah Kakak Beradik Baya dan Bara Menjalani Hidup Sebagai Pengamen Jalanan
“Aku gak papa kok,” elakku. Mana bisa aku menyerah sedangkan aku juga turut menjadi inisiator kegiatan ini, malu banget pasti.
“Ya udah.” Kei berjalan lagi, tapi langkahnya sedikit pelan. Mungkin perasaanku saja, tapi dia memang seolah tidak ingin meninggalkanku.
“Auh!” Aku salah mengira dahan di depanku yang ternyata ranting rapuh untuk kujadikan pegangan, aku terpeleset. Tanganku rasanya perih dan penuh lumpur karena menahan badanku saat tergelincir ke bawah.
“Kamu nggak papa Keira? Bisa bangun?” Kei yang memang tak jauh dariku langsung menghampiri. Aku mengangguk.
“Ayo!” Kei mengulurkan tangannya. “Tunggu, ...” Aku merasakan ada air mengalir dari tebing di sebelah kiriku. “ Mau cuci tangan dulu.”
Kei langsung melihat air yang kumaksud, ia terperanjat.
“Keira, kamu turun!”
“Kenapa tiba-tiba?” tanyaku bingung. Sorot matanya tajam, seolah menyadari ada yang tidak beres di sini. Ia melihat sekitar, tepat saat segerombolan burung terbang menjauh dari puncak bukit. Kei bergegas lari ke atas. “Teman-teman, kita tunda kegiatannya. Cepat turun!” perintahnya. Ia berbalik lagi, melihat ke arahku, mengisyaratkan aku untuk turun dengan tangannya.
“Kenapa?”
“Ada apa?” Tanya yang lain kebingungan.