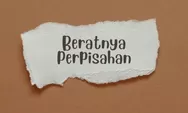Akhirnya aku diam dan mendengarkannya bercerita sepanjang perjalanan.
"Dulu si Bagja nyaris aja mau diambil dan dirusak orang. Ada teman sekolah yang ganggu ayah dan mau mukul ayah waktu itu, dia maksa minta uang tapi ayah enggak kasih ...."
"Terus gimana, Yah?" tanyaku yang lagi-lagi penasaran.
"Baru saja tadi dibilang, kan. Sabar, Embun."
Baca Juga: Ulasan Buku Pendidikan Kaum Tertindas: Kritik Paulo Freire Atas Pendidikan 'Gaya Bank'
"Iya maaf, Yah. Habis Embun penasaran kisah si Bagja dan cinta orangtua Embun."
Ayah menggeleng kecil dan aku bisa mendengar dia sedikit tertawa, karena aku terlalu cerewet dan tidak sabaran. Setelah itu dia melanjutkan kisah si Bagja.
"Karena ayah enggak kasih uang ke mereka, si Bagja yang jadi sasaran. Tapi sebelum itu terjadi seseorang nolongin ayah, dia perempuan dan bilang sama teman yang ganggu ayah untuk berhenti atau dilaporkan ke guru. Karena takut, mereka pun pergi."
Aku sudah bisa menduga bahwa penyelamat itu adalah ibuku. Siapa lagi kalau bukan Ibu? Tidak mungkin orang lain.
"Namanya Lesiha, panggilannya Esih ibumu. Sejak saat itu kami berteman dekat. Dari situlah ayah jatuh cinta pada ibumu sampai sekarang, dia juga yang kasih nama sepeda ontel ayah si Bagja yang dalam bahasa Sunda artinya bahagia." Ayah terdiam sejenak, dia berhenti bercerita.
Aku mengusap punggungnya pelan, lelaki yang masih mengayuh sepeda dan aku tahu dia sedang berusaha menahan tangisannya.
"Ibumu berharap mungkin itu adalah doa, agar ke mana pun ayah pergi mengayuh si Bagja sepeda itu akan membawa kebahagiaan ...." Ayah berhenti sejenak, seperti ada sesuatu yang menahannya untuk bercerita.
"Dan Esih benar kebahagiaan itu tetap ada terbukti dengan hadirnya gadis bernama Embun anak dan buah cinta kami," ucapnya yang membuatku tak sadar mulai menangis.