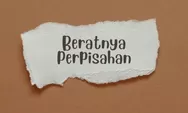Maka tak heran, jika malam tiba lampu-lampu mulai menyala dengan terangnya seperti cahaya kunang-kunang yang berpendar.
Melihat itu semua, Marno seakan-akan terlempar ke masa-masa saat ia masih hidup di sebuah desa dan bermain di sawah mbahnya.
“Kalau saja apa, Kekasihku?”
“Kalau saja ada suara jangkrik mengerik dan beberapa katak menyanyi dari luar sana.”
“Lantas?”
“Tidak apa-apa. Itu kan membuat aku lebih senang sedikit.”
“Kau anak desa yang sentimental!”
Percakapan dengan Jane ini menandakan Marno amat merindukan desa yang kini dia hanyalah seonggok daging kecil yang berjalan di tengah padatnya manusia yang berlalu-lalang.
Baca Juga: Cerpen Teknologi: Kisah Perkembangan Prosesor X86 dalam Revolusi Teknologi Komputer
Hanyalah kenangan masa kecilnya yang menjadi pelipur lara akan kegundahan hatinya.
Cahaya kunang-kunang yang berpendar-pendar tak dapat ia temukan di Manhattan tempat tinggalnya saat ini, hanyalah lampu-lampu gedung pencakar langit yang selalu menyala.
Ya, Marno, seorang yang tumbuh di desa dengan kenangan masa kecil yang masih membekas.
Kini, hanya itu yang ia punya, orang desa yang hidup di sebuah kota dengan tingkat kebisingan dan kesibukan tak tertandingi.
Hidup dengan gaya kota ala Barat. Minum dengan Scotch. Tetapi orang desa tetaplah orang desa yang masih melekat dalam dirinya.
Sejauh apapun Marno saat ini, desa baginya mempunyai apa yang tidak dipunyai sebuah kota.